-
Continue reading →: Sinergi Teori Hebdige dan Butler dalam Melawan Hegemoni Patriarki pada Pemilu Eksekutif Indonesia Lewat Reproduksi Mitos Tandingan
Sinergi pemikiran subkultur Hebdige dan performativitas gender ala Butler dalam mereproduksi mitos tandingan tentang pencapaian domestik sebagai strategi politisi perempuan melawan hegemoni patriarki di pemilu eksekutif.
-
Continue reading →: Sintesa Pertanyaan Penelitian SAP 9-14 Perspektif Teori Media 2025
SAP CPMK Pertanyaan Penelitian Pertanyaan Penelitian (Sintesis) 9 Teori Media dan Kajian Budaya Pertanyaan Utama: Bagaimana politisi perempuan mereproduksi narasi tentang tugas-tugas dan pencapaian domestik sebagai mitos tandingan yang terwakilkan secara kultural untuk melawan hegemoni patriarki dalam konteks pemilihan eksekutif? Pertanyaan Pendukung:Sejauh mana pencapaian domestik dapat dianalisis melalui lensa wacana dan…
-
Continue reading →: Integrasi Rute Periferal, Skema Personal, dan Kultivasi untuk Mereproduksi Mitos Tandingan Pencapaian Domestik di Media dalam Melawan Hegemoni Patriarki pada Pemilu Eksekutif
Penelitian ini hendak melihat bagaimana politisi perempuan mengupayakan strategi untuk melawan kekerasan simbolik di media. Bentuk perlawanan tersebut ditampilkan melalui mitos tentang pencapaian domestik sebagai narasi tandingan yang melawan narasi dominan patriarki dalam pemilu eksekutif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan gagasan perlawanan kekerasan simbolik yang ditawarkan oleh Perse (2008).…
-
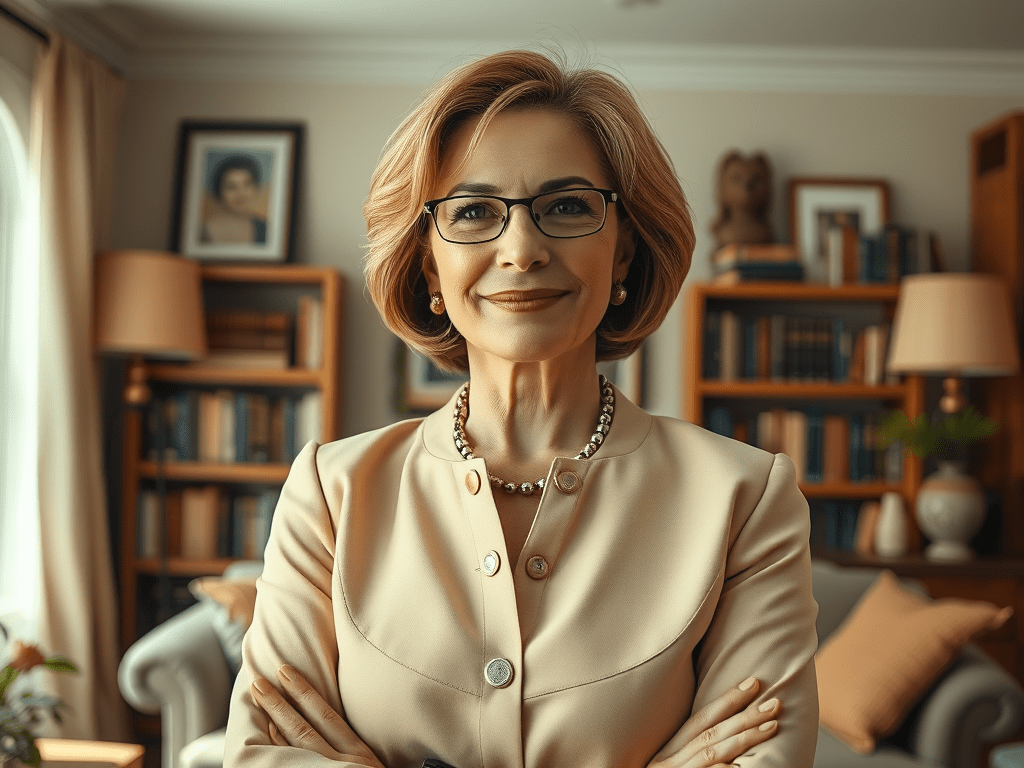 Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Dalam Paradigma Postmodern
Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Dalam Paradigma PostmodernStrategi politisi perempuan mereproduksi mitos tandingan untuk melawan hegemoni patriarki dengan menggunakan pendekatan postmodern
-
 Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Tentang Pencapaian Domestik dalam Perspektif Realitas Hiper Baudrillard dan Masyarakat Jaringan Castells
Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Tentang Pencapaian Domestik dalam Perspektif Realitas Hiper Baudrillard dan Masyarakat Jaringan CastellsPencapaian domestik menjadi mitos tandingan yang dibentuk dalam ruang simulasi masyarakat jaringan untuk melawan hegemoni patriarki.
-
 Continue reading →: Eksplorasi Strategi Politisi Perempuan dalam Menciptakan Mitos Tandingan tentang Pencapaian Domestik Lewat Pendekatan Subversivitas Performatif Gender Judith Butler
Continue reading →: Eksplorasi Strategi Politisi Perempuan dalam Menciptakan Mitos Tandingan tentang Pencapaian Domestik Lewat Pendekatan Subversivitas Performatif Gender Judith ButlerMereproduksi narasi domestik sebagai mitos tandingan dalam melawan hegemoni patriarki dengan pendekatan subversifitas performatif gender Judith Butler.
-
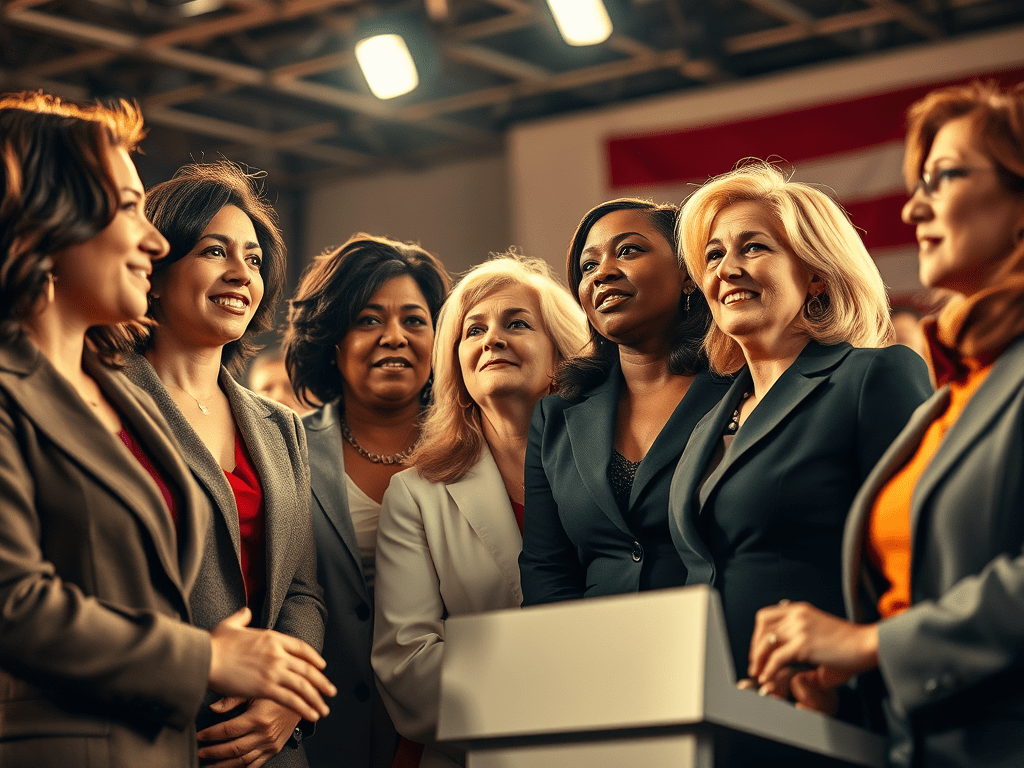 Continue reading →: Strategi Politisi Perempuan Dalam Memproduksi Mitos Tandingan Untuk Melawan Hegemoni Patriarki: Sebuah Pendekatan Interaksionis
Continue reading →: Strategi Politisi Perempuan Dalam Memproduksi Mitos Tandingan Untuk Melawan Hegemoni Patriarki: Sebuah Pendekatan InteraksionisStrategi politisi perempuan untuk membuat simbol-simbol baru dalam bahasa feminin untuk melawan mitos patriarki.
-
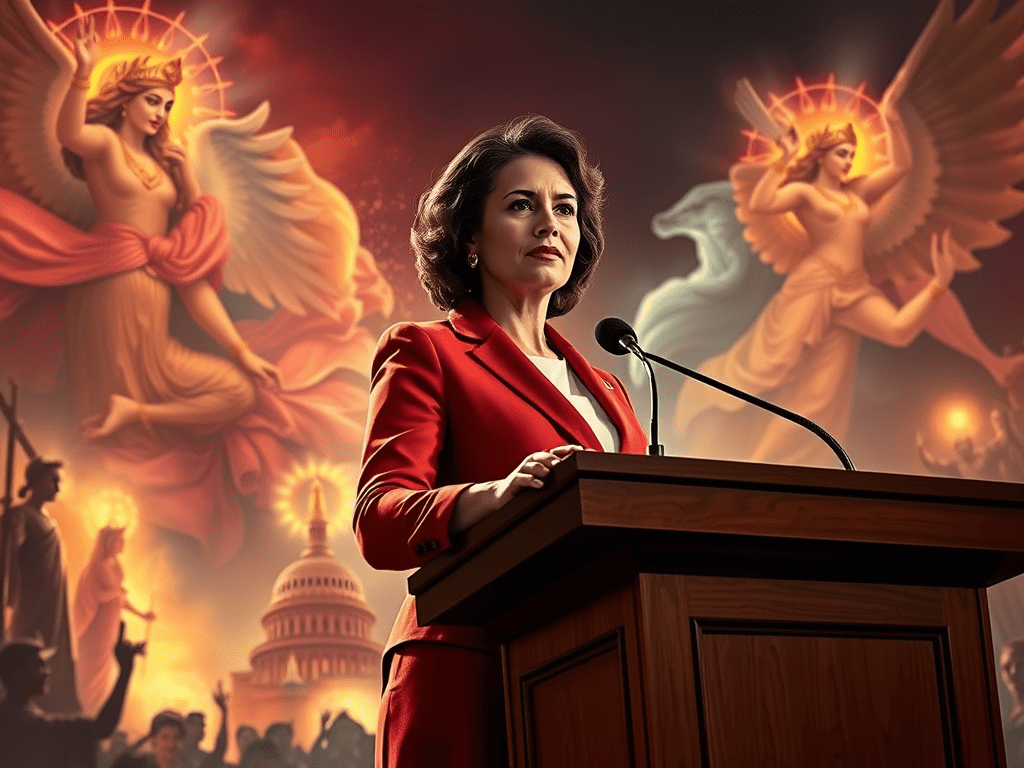 Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Sebagai Strategi Perlawanan Politisi Perempuan Terhadap Hegemoni Patriarki
Continue reading →: Reproduksi Mitos Tandingan Sebagai Strategi Perlawanan Politisi Perempuan Terhadap Hegemoni PatriarkiPenciptaan mitos tandingan sebagai bentuk perlawanan politisi perempuan terhadap hegemoni patriarki.
-
Continue reading →: Sintesis Pertanyaan SAP 2-6 Perspektif Teori Media
SAP CPMK Pertanyaan Penelitian Pertanyaan Penelitian (Sintesis) 2 Teori Media dan Praktik Pertanyaan Utama: Bagaimana para agen politik (kandidat perempuan, tim kampanye, dan pemilih) merekonstruksi narasi politik baru untuk mempengaruhi habitus pemilih yang terpengaruh narasi lama yang sangat patriarkis dan bias gender? Pertanyaan Pendukung:(1) Bagaimana merekonstruksi ‘formula’ narasi politik baru…
-
Continue reading →: Merekonstruksi Narasi Politik Untuk Meningkatkan Elektabilitas Perempuan Pada Pemilu Eksekutif: Sebuah Pendekatan Dengan Kerangka Teori Ekonomi Politik Kultural
Penafian: Peneliti menggunakan kecerdasan buatan Notebook LM sebagai platform diskusi dan pembuatan tabel komparasi bahan bacaan. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana mekanisme produksi dan pelanggengan wacana patriarki tentang kepemimpinan perempuan dapat direkonstruksi untuk tujuan meningkatkan elektabilitas pemimpin perempuan pada pemilu eksekutif. Oleh karenanya, penelitian ini menegaskan posisi teoretisnya dengan menggunakan pendekatan…
Hello,
I’m Elle Zahra

Mari Melek Media menjadi upaya literasi media bagi Elle untuk dapat membagikan, berdiskusi, dan bertukar pikiran mengenai isu-isu yang terjadi di media, terutama media digital.
Let’s connect
Join the fun!
Stay updated with our latest tutorials and ideas by joining our newsletter.